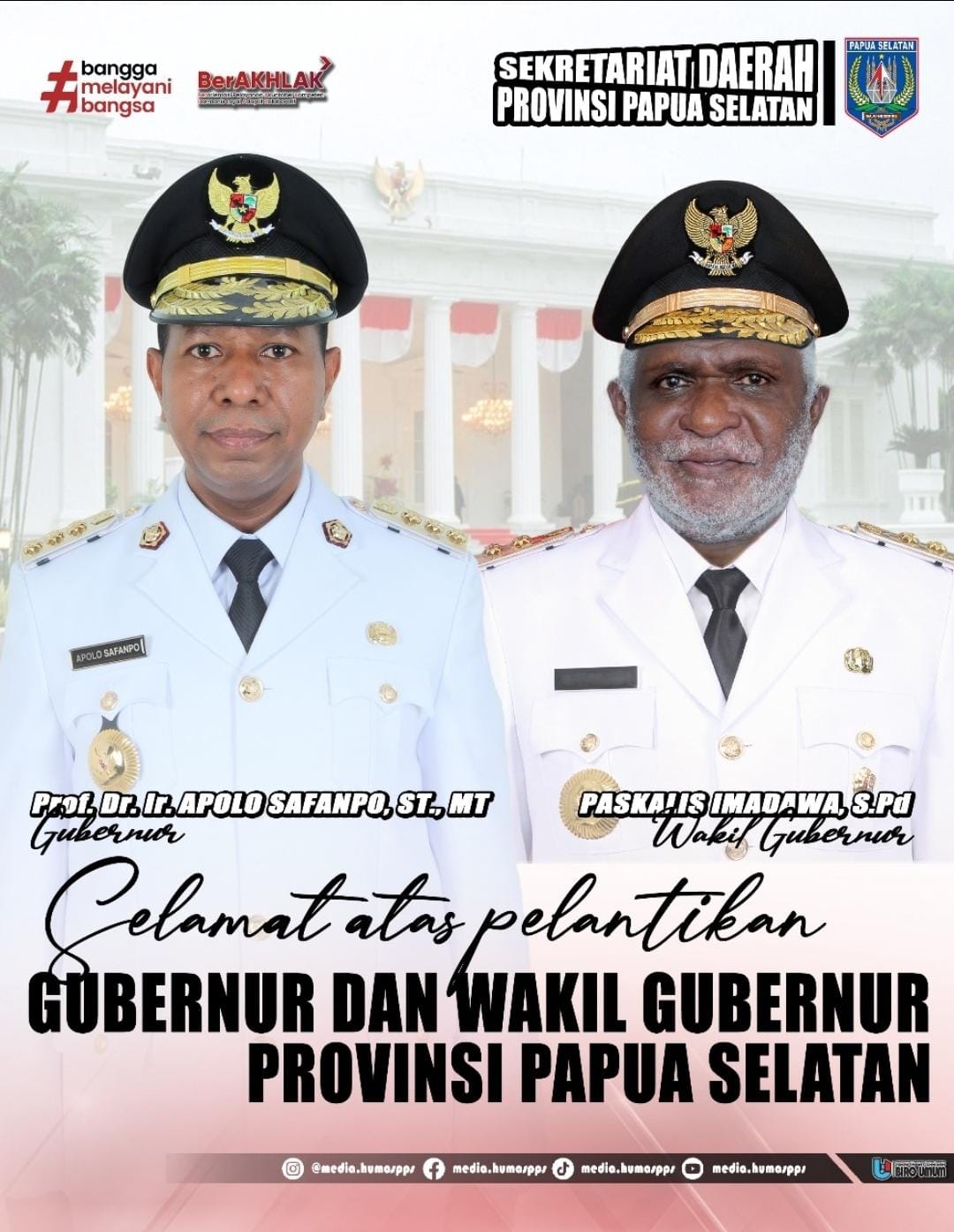Oleh : Yohanis Elia Sugianto
Papua Selatan, sebuah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, ironisnya menjadi panggung bagi konflik agraria yang mendalam dan berkepanjangan. Di jantung konflik ini terdapat benturan fundamental antara dua pandangan dunia: pandangan korporasi dan negara yang melihat tanah sebagai komoditas ekonomi dan aset produksi, dengan pandangan masyarakat adat yang memaknai tanah sebagai ruang hidup, identitas, dan kosmos spiritual. Penyerobotan tanah adat oleh perusahaan-perusahaan produksi, khususnya perkebunan kelapa sawit skala besar, bukan sekadar sengketa kepemilikan, melainkan sebuah tindakan pemiskinan struktural dan penghapusan kebudayaan secara sistematis.
Potret Kasus: Luka di Tanah Marind dan Auyu
Beragam kasus penyerobotan tanah adat menjadi bukti nyata dari tragedi ini. Salah satu contoh paling monumental adalah Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke. Proyek raksasa ini telah membuka pintu bagi puluhan perusahaan untuk mengakuisisi jutaan hektar lahan. Namun, proses akuisisi ini sering kali mengabaikan hak ulayat masyarakat adat, terutama suku Marind Anim. Laporan dari berbagai organisasi non-pemerintah menunjukkan bahwa proses konsultasi kerap bersifat manipulatif. Masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit, diiming-imingi kompensasi yang tidak seberapa, tanpa pemahaman penuh bahwa mereka akan kehilangan akses permanen terhadap hutan sagu, sumber air, dan lokasi keramat yang menjadi tumpuan hidup mereka selama berabad-abad.
Di wilayah lain seperti di Kabupaten Boven Digoel, suku Auyu dan Wambon juga menghadapi ancaman serupa. Perusahaan-perusahaan, dengan berbekal Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) dari negara, merasa memiliki legitimasi untuk melakukan pembukaan lahan. Padahal, izin tersebut sering kali tumpang tindih dengan wilayah adat yang tidak pernah dipetakan atau diakui secara formal oleh negara. Akibatnya, hutan yang menjadi “supermarket” dan “apotek” bagi masyarakat adat hilang, digantikan oleh hamparan monokultur kelapa sawit. Konflik pun tak terhindarkan, yang sayangnya sering kali dihadapi dengan pendekatan keamanan.
Analisis Filosofis-Kebudayaan: Tanah sebagai Ruang Hidup
Untuk memahami kedalaman masalah ini, kita harus bergerak melampaui analisis hukum-formal dan masuk ke dalam ranah filsafat kebudayaan. Paradigma pembangunan yang diusung negara secara implisit berakar pada filsafat kepemilikan Barat, khususnya pemikiran John Locke. Locke berpendapat bahwa properti pribadi lahir ketika manusia “mencampurkan tenaganya” dengan alam. Tanah yang tidak “digarap” secara intensif dianggap “terlantar” (wasteland) yang sah untuk diambil alih. Cara pandang inilah yang melegitimasi konversi hutan adat menjadi perkebunan.
Namun, pandangan ini bertabrakan dengan filsafat kebudayaan masyarakat adat. Filsuf Ernst Cassirer menyatakan bahwa manusia adalah animal symbolicum (hewan yang menggunakan simbol). Bagi masyarakat adat, tanah bukanlah objek mati, melainkan sebuah jalinan simbol yang hidup. Merampas tanah mereka berarti merobek tatanan simbolik yang menjadi dasar keberadaan mereka. Di sinilah relevansi pemikiran filsuf Charles Taylor tentang “Politik Pengakuan” (The Politics of Recognition) menjadi krusial. Kegagalan negara untuk mengakui hak ulayat masyarakat adat secara substantif adalah sebuah bentuk “kesalahan pengakuan” (misrecognition) yang menyerang martabat dan harga diri sebuah komunitas budaya.
Urgensi Penghargaan Hak Ulayat dalam Bingkai UUD 1945 dan Pancasila
Konflik ini sejatinya merupakan pengkhianatan terhadap fondasi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), secara tegas menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya…”. Pancasila sebagai falsafah negara juga dilanggar secara fundamental. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercabik ketika masyarakat adat kehilangan sumber kehidupannya. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi slogan kosong ketika pembangunan hanya menguntungkan segelintir elite korporasi.
Menghadapi krisis ini, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah. Institusi moral seperti gereja memiliki peran sentral sebagai suara kenabian dan pendamping umat. Dalam konteks ini, Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke (KAME) di bawah kepemimpinan Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, menunjukkan sebuah model pendekatan yang dapat menjadi tolak ukur, meskipun kompleks dan mengundang dialog kritis.
Kepemimpinan Mgr. Mandagi menekankan pentingnya pembangunan yang “memanusiakan manusia”. Sikap ini tecermin dari dukungannya terhadap program-program yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti proyek lumbung pangan (food estate), dengan syarat utama bahwa proyek tersebut tidak boleh menyengsarakan rakyat dan harus dilakukan melalui dialog yang tulus. Namun, di sisi lain, dukungan ini memicu perdebatan, karena sebagian kalangan masyarakat sipil dan adat sendiri merasa proyek-proyek skala besar inilah yang justru menjadi akar masalah perampasan tanah.
Di sinilah letak relevansi ajaran sosial Gereja Katolik secara universal sebagai kompas moral. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si, menyerukan sebuah “ekologi integral” yang menghubungkan kepedulian terhadap bumi dengan keadilan bagi kaum miskin dan terpinggirkan. Ensiklik ini secara tegas mengkritik paradigma teknokratis yang melihat alam hanya sebagai objek profit dan menyerukan pertobatan ekologis.
Dengan demikian, langkah-langkah yang dapat dijadikan tolak ukur dari dinamika Keuskupan Agung Merauke adalah sebagai berikut:
- Menjadi Jembatan Dialog
Gereja, sebagaimana dipraktikkan KAME, memposisikan diri sebagai mediator antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Peran ini krusial untuk memastikan suara masyarakat yang paling rentan didengar dan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas.
- Advokasi Berbasis Ajaran Sosial
Langkah Gereja harus secara konsisten didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran sosialnya, terutama yang tertuang dalam Laudato Si’. Artinya, setiap kebijakan pembangunan harus diuji dengan pertanyaan mendasar: Apakah ini menghormati martabat manusia? Apakah ini menjaga keutuhan ciptaan? Apakah ini berpihak pada kaum miskin? Ini menjadi standar moral yang harus dipegang teguh dalam setiap advokasi.
- Pastoral Ekologis dan Pemberdayaan Umat
Keuskupan, melalui komisi-komisi seperti Komisi Keadilan dan Perdamaian (SKP), berperan penting dalam menyadarkan umat akan hak-hak mereka dan tanggung jawab ekologis. Ini mencakup pendampingan hukum bagi komunitas yang tanahnya dirampas serta pengembangan program ekonomi alternatif yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal, sebagai tandingan bagi model ekonomi ekstraktif.
Pemerintah pusat dan daerah dapat belajar dari pendekatan ini. Kebijakan tidak boleh dirumuskan secara monolitik dari atas, melainkan harus melibatkan institusi-institusi lokal yang dipercaya masyarakat.
Langkah-langkah pemerintah yang harus diambil adalah:
Moratorium dan Evaluasi Izin
Memberlakukan moratorium total atas izin-izin baru perkebunan skala besar dan mengevaluasi izin yang telah terbit dengan melibatkan partisipasi gereja dan masyarakat sipil.
Percepatan Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat
Pemerintah daerah harus proaktif memetakan wilayah adat, bekerja sama dengan komunitas dan didampingi oleh pihak-pihak tepercaya seperti gereja.
Menyegerakan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Memberikan payung hukum nasional yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.
Pada akhirnya, menyelesaikan konflik tanah di Papua Selatan menuntut sebuah pergeseran paradigma. Negara harus berhenti memandang dirinya sebagai satu-satunya pemilik sah atas tanah dan mulai bertindak sebagai fasilitator keadilan yang menghormati pluralisme hukum dan kebudayaan. Peran institusi moral seperti Keuskupan Agung Merauke, dengan segala dinamikanya, menunjukkan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal hukum dan ekonomi, tetapi juga soal panggilan moral dan spiritual untuk merawat “rumah kita bersama”. Tanpa pengakuan yang tulus terhadap masyarakat adat sebagai subjek yang setara, pembangunan hanya akan menjadi eufemisme bagi penjajahan gaya baru, dan Pancasila serta UUD 1945 akan tetap menjadi teks suci yang tak pernah membumi di Tanah Papua.
Daftar Pustaka
Cassirer, Ernst. An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. New Haven: Yale University Press, 1944.
Forest Peoples Programme. The Human Rights Impacts of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. Moreton-in-Marsh, 2015.
Fransiskus, Paus. Ensiklik Laudato Si’: Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama. Vatikan, 2015.
Locke, John. Second Treatise of Government. Indianapolis: Hackett Publishing, 1980.
Taylor, Charles. “The Politics of Recognition.” Dalam Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, disunting oleh Amy Gutmann. Princeton: Princeton University Press, 1994.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.