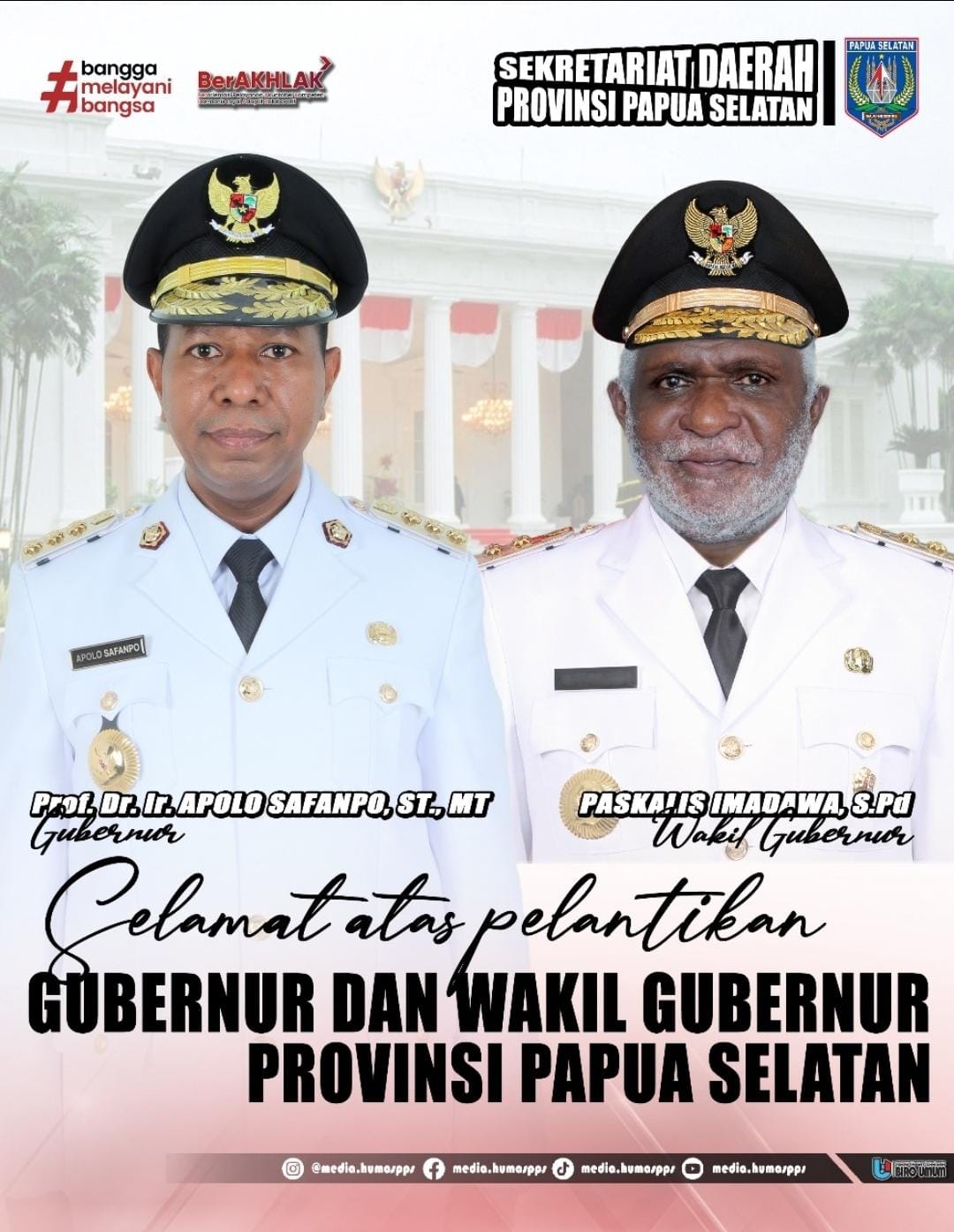Oleh : Yohanis Elia Sugianto
Menakar visi Panglima Tertinggi & Harapan atas Masa Depan TNI Sebagai Guardian Bangsa
Perkembangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan sebuah lintasan yang melampaui sekadar modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Di balik deru mesin jet tempur baru dan siluet kapal perang modern, terdapat sebuah proses pematangan filosofis yang, jika kita amati secara saksama, mendekati sebuah ideal klasik tentang peran angkatan bersenjata. Perkembangan ini, yang ditandai oleh peningkatan profesionalisme, fokus pada kesejahteraan prajurit, dan postur diplomasi pertahanan yang aktif, dapat kita pahami secara lebih mendalam melalui kacamata filsafat, khususnya dari pemikiran Plato tentang “Guardian” atau Kelas Penjaga.
Dalam magnum opusnya, Politeia (Republik), Plato menguraikan sebuah negara ideal yang ditopang oleh kelas-kelas fungsional, di mana yang paling krusial adalah para Guardian.[1] Mereka bukanlah sekadar tentara bayaran atau mesin perang, melainkan pelindung negara yang dididik secara holistik dalam filsafat, musik, dan gimnastik untuk membentuk jiwa yang seimbang: berani namun lembut, tangguh namun bijaksana. Raison d’être mereka bukanlah menaklukkan, melainkan menjaga keutuhan, keadilan, dan harmoni negara dari ancaman internal maupun eksternal. Di titik inilah kita dapat melihat paralel yang positif. Fokus kebijakan pertahanan saat ini pada peningkatan kualitas hidup dan pendidikan prajurit adalah sebuah upaya sadar atau tidak sadar untuk membentuk Guardian modern. Prajurit yang sejahtera dan terdidik tidak hanya mahir menggunakan senjata, tetapi juga memiliki aretē (keutamaan atau keunggulan) yang membuatnya menjadi pelindung sejati konstitusi dan rakyat.
Modernisasi alutsista yang masif, dengan demikian, bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana material bagi para Guardian ini untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Sebuah negara maritim yang luas seperti Indonesia tentu membutuhkan “gigi” yang tajam untuk melindungi kedaulatannya. Namun, nilai sesungguhnya tidak terletak pada ketajaman gigi itu semata, melainkan pada kebijaksanaan yang mengendalikannya. Di sinilah relevansi pemikiran strategis militer klasik dari Carl von Clausewitz menemukan tempatnya. Clausewitz, dalam karyanya yang monumental Vom Kriege (Tentang Perang), menyatakan bahwa “perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain”.[2] Pernyataan ini menegaskan supremasi sipil dan tujuan politik atas tindakan militer. Kekuatan militer, seberapa pun dahsyatnya, adalah instrumen negara, bukan tuannya.
Kombinasi antara idealisme Plato dan realisme Clausewitz ini memberikan kerangka yang kokoh untuk menilai perkembangan TNI. Di satu sisi, TNI dibentuk menjadi Guardian yang berkeutamaan. Di sisi lain, kekuatannya harus secara presisi menjadi alat bagi “politik bebas aktif” Indonesia di panggung dunia. Kekuatan TNI yang disegani bukan untuk memulai konflik, melainkan untuk memberikan bobot dan kredibilitas pada diplomasi Indonesia. Ia menjadi daya gentar (deterrence) yang memungkinkan para diplomat kita berbicara dengan suara yang lebih lantang, menengahi konflik dengan posisi yang lebih kuat, dan pada akhirnya, memperjuangkan perdamaian dari posisi yang berdaulat, bukan dari posisi yang lemah.
Maka, harapan ke depan tertumpu pada pundak sang Panglima Tertinggi: Presiden Republik Indonesia. Peran Presiden di sini melampaui sekadar fungsi administratif atau seremonial; ia adalah perwujudan modern dari konsep “Raja-Filsuf” (Philosopher King) yang digagas Plato.[3] Seorang Raja-Filsuf adalah pemimpin yang memerintah bukan berdasarkan hasrat kekuasaan, melainkan berdasarkan pemahaman mendalam akan kebaikan, kebenaran, dan keadilan bagi seluruh polis atau negara. Ia adalah sosok yang memiliki phronesis atau kebijaksanaan praktis untuk mengarahkan seluruh elemen negara, termasuk para Guardian, menuju tujuan bersama.
Dalam konteks kekinian, Presiden sebagai Panglima Tertinggi harus mampu menjadi sang Raja-Filsuf yang mengarahkan instrumen pertahanan (TNI yang modern) untuk tujuan-tujuan politik yang luhur. Tugas beliau adalah memastikan bahwa kekuatan yang terus bertumbuh ini digunakan untuk menjembatani, bukan memperlebar, jurang konflik, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Kekuatan militer harus menjadi penopang utama bagi peran Indonesia sebagai juru damai di ASEAN, sebagai suara penyeimbang di antara kekuatan-kekuatan besar dunia, dan sebagai pelindung bagi negara-negara yang lebih lemah.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi TNI tidak hanya diukur dari jumlah alutsista yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana kekuatan itu mampu menopang cita-cita bangsa untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Momentum positif yang ada saat ini adalah kesempatan emas. Dengan TNI yang semakin profesional sebagai Guardian dan Presiden yang menjalankan perannya sebagai Panglima Tertinggi yang bijaksana, Indonesia tidak hanya akan aman, tetapi juga akan menjadi mercusuar harapan dan stabilitas di tengah dunia yang bergejolak.
[1] Plato. The Republic. (Circa 375 BC). Buku II, 374e-376e & Buku III, 412b-414b. Dalam bagian ini, Plato secara detail membahas seleksi, pendidikan, dan peran dari Kelas Penjaga (Guardians) dalam struktur negara idealnya.
[2] Clausewitz, Carl von. On War. (1832). Buku I, Bab 1, Bagian 24. Aforisme ini merupakan inti dari seluruh tesis Clausewitz yang menempatkan perang sebagai subordinat dari tujuan politik.
[3] Plato. The Republic. (Circa 375 BC). Buku V, 473d. Di sini Plato mengajukan dalilnya yang paling terkenal: “Sampai para filsuf menjadi raja di dunia, atau sampai mereka yang kita sebut raja dan penguasa benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi filsuf… kota-kota tidak akan pernah beristirahat dari kejahatan.”