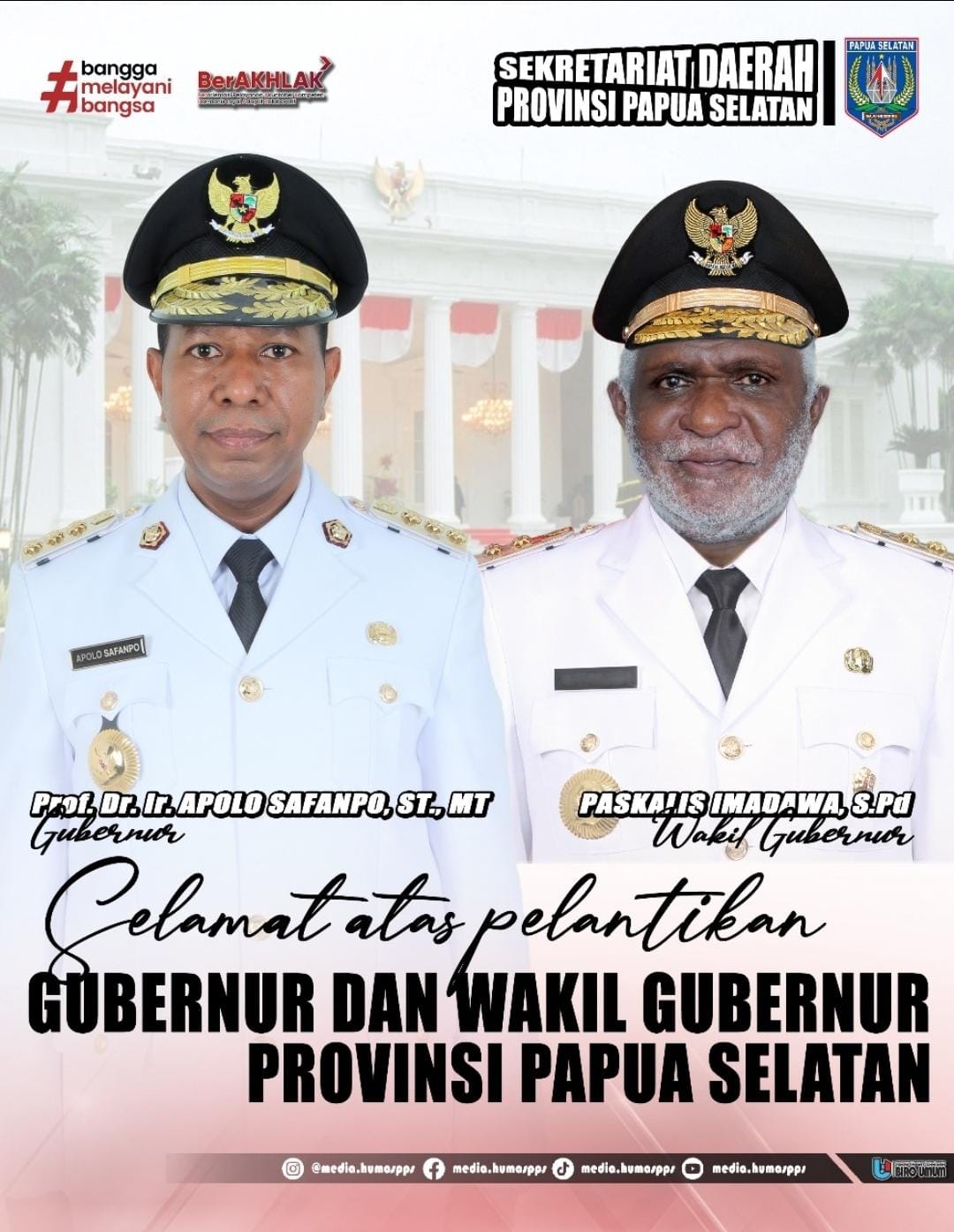Dari Teks Sejarah Menjadi Manifesto Kompetensi Pemuda Papua Selatan
Oleh : Yohanis Elia Sugianto
Setiap tahun, 28 Oktober menjelma menjadi sebuah panggung ritual kebangsaan. Kita mengulang tiga ikrar: satu tanah air, satu bangsa, satu Bahasa, sebagai bagian dari apa yang oleh sejarawan disebut sebagai “penciptaan tradisi” untuk memperkuat imajinasi kolektif.[1] Namun, di luar auditorium berpendingin udara dan upacara bendera, di tengah derap modernisasi yang bising dan tak kenal ampun, sebuah pertanyaan fundamental menggugat kita: Apakah Sumpah Pemuda masih relevan? Atau, ia telah menjadi naskah tua yang tergeletak bisu; sebuah artefak sejarah yang maknanya telah beku, tak lagi mampu menyapa realitas kekinian?
Bagi generasi muda di Papua Selatan, pertanyaan ini bukanlah sekadar renungan akademis. Ia adalah denyut nadi eksistensial. Mereka kini hidup dalam konstelasi paradoksal. Di satu sisi, janji kesejahteraan membentang lebar seiring ditetapkannya status Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2022. Pembangunan infrastruktur fisik—kantor gubernur megah di Merauke, pembukaan jalan yang membelah isolasi Mappi dan Asmat, peningkatan pelabuhan di Boven Digoel berlangsung masif.[2] Di sisi lain, ancaman alienasi dan marginalisasi terasa begitu nyata. Pembangunan fisik yang cepat ini tidak serta-merta diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal.[3] Kompetisi di pasar kerja, baik di sektor birokrasi maupun swasta, menjadi luar biasa ketat dengan masuknya tenaga kerja terampil dari luar Papua.
Dalam situasi pelik inilah terjepit antara harapan DOB dan kecemasan akan keterasingan, Sumpah Pemuda justru menemukan urgensi barunya. Ia harus diselamatkan dari pembacaan yang beku dan ritualistik. Ia harus dibaca ulang, bukan sebagai fosil, melainkan sebagai teks yang hidup. Untuk melakukannya, kita memerlukan sebuah alat bedah filosofis: hermeneutika.
Secara khusus, hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer menawarkan jalan keluar dari kebuntuan ini. Gadamer, dalam mahakaryanya Truth and Method, menolak pandangan historisisme yang naif; bahwa kita bisa menanggalkan “kekinian” kita untuk memahami sebuah teks “apa adanya” sesuai niat asli penulisnya.[4] Bagi Gadamer, pemahaman selalu bersifat historis. Kita tidak pernah mendekati teks dengan kepala kosong, melainkan selalu membawa “pra-pemahaman” atau “prasangka” (Vorurteil) yang dibentuk oleh situasi kita saat ini.
Pemahaman, bagi Gadamer, adalah sebuah “peleburan horizon” (Horizontverschmelzung).[5] Ini adalah sebuah proses dialogis yang produktif antara “horizon” teks (dunia Sumpah Pemuda 1928 dengan semangat anti-kolonialisme) dengan “horizon” pembaca (dunia pemuda Papua Selatan 2025 dengan kecemasan akan kesenjangan SDM). Makna tidak ditemukan dengan “kembali ke tahun 1928”, melainkan diciptakan dalam ketegangan antara apa yang dikatakan teks itu dulu dan apa yang ditanyakannya kepada kita sekarang. Pemuda Papua Selatan, dengan segala pra-pemahaman mereka, justru memiliki posisi istimewa untuk melakukan dialog ini. Mari kita bedah ketiga sumpah itu.
Fusi Horizon I: “Satu Tanah Air” sebagai Kedaulatan Subjek Pembangunan
Horizon Teks (1928): Ikrar “Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia” adalah sebuah proklamasi geopolitik. Dalam konteks cengkeraman kolonialisme Hindia Belanda, para Jong dari berbagai pulau menyatakan bahwa tanah yang mereka pijak, meski terpisah lautan, adalah satu kesatuan yang harus direbut kedaulatannya.[6] Fokusnya jelas: teritorial, politis, dan anti-kolonial.
Horizon Pembaca (Papua Selatan 2025): Pertanyaan yang diajukan pemuda Papua Selatan hari ini jauh lebih menusuk: “Apa artinya memiliki ‘tanah air’ jika kami hanya menjadi penonton di atasnya? Apa makna ‘tanah’ kami jika ia dikeruk untuk pembangunan infrastruktur massif yang seringkali mengabaikan hak ulayat namun yang mengisi pos-pos strategis dan menikmati kue ekonomi adalah orang lain?”[7]Ini adalah ketakutan menjadi “objek” pembangunan, sebuah pola yang telah lama dikritik dalam studi pembangunan di Papua yang cenderung top-down.[8]
Fusi Horizon (Makna Baru): Dialog antara dua horizon ini melahirkan makna baru yang kuat. “Satu Tanah Air” bagi pemuda Papua Selatan bergeser dari kedaulatan teritorial semata menjadi kedaulatan atas proses pembangunan. Ini adalah sebuah sumpah eksistensial. “Tanah Air” bukan lagi sekadar geografi yang harus dipertahankan dari musuh luar, melainkan sebuah ruang hidup yang harus dikuasai secara substantif.
Ikrar ini menjadi manifesto untuk menolak menjadi objek. Ia adalah tuntutan untuk menjadi subjek utama pembangunan. Jika tanah ini adalah tumpah darah kita, maka pemuda OAP-lah yang harus berada di garda terdepan dalam mengelola proyek-proyek DOB, mengisi birokrasi, dan memimpin sektor swasta. Sumpah ini adalah mandat untuk memastikan bahwa setiap jengkal pembangunan di Papua Selatan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat Papua, sejalan dengan semangat dasar Otonomi Khusus (Otsus).[9]
Fusi Horizon II: “Satu Bangsa” sebagai Proyek Keadilan Sosial
Horizon Teks (1928): Ikrar “Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia” adalah sebuah kontrak sosial revolusioner. Ia adalah kesediaan untuk melampaui identitas-identitas primer (Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon) demi sebuah imajinasi kolektif baru. Musuh bersamanya jelas: kolonialisme. Persatuan adalah senjata.
Horizon Pembaca (Papua Selatan 2025): Konteks hari ini terbalik. Tantangannya bukan musuh eksternal, melainkan kompetisi internal yang timpang. Realitas DOB menghadirkan persaingan ketat antara Orang Asli Papua (OAP) dengan pendatang (non-OAP) yang seringkali memiliki modal (pendidikan, jaringan, kapital) yang jauh lebih tinggi.[10] Pertanyaannya menjadi: “Bagaimana kita bisa bicara ‘satu bangsa’ jika dalam praktiknya kita tidak memulai dari garis start yang sama? Bagaimana ‘satu bangsa’ bisa terwujud jika yang terjadi adalah dominasi struktural, bukan kolaborasi setara?”
Fusi Horizon (Makna Baru): Makna “Satu Bangsa” bergeser secara radikal. Ia bukan lagi sekadar deklarasi persatuan, melainkan sebuah tuntutan atas proyek keadilan sosial. Jika kita benar-benar “satu bangsa”, maka realitas ketimpangan, khususnya kesenjangan SDM dan ekonomi tidak bisa dibiarkan berjalan atas nama “kompetisi bebas” yang Darwinian.
Ikrar ini menjadi landasan moral dan yuridis terkuat untuk menuntut keberpihakan atau afirmasi. Ini bukan permintaan “belas kasihan”, melainkan implementasi dari mandat konstitusional dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otsus, yang secara eksplisit mengamanatkan pemberdayaan dan afirmasi bagi OAP.[11] “Satu Bangsa” hari ini berarti bahwa seluruh komponen bangsa, terutama negara (melalui regulasi DOB) dan sektor swasta, memiliki kewajiban historis dan moral untuk mengangkat pemuda OAP. Solidaritas bukan lagi basa-basi, tapi sebuah keharusan struktural untuk memastikan modernisasi tidak berujung pada marginalisasi.[12]
Fusi Horizon III: “Satu Bahasa” sebagai Sumpah Penguasaan Kompetensi
Horizon Teks (1928): Ikrar “Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” adalah sebuah keputusan strategis-kultural. Di tengah ratusan bahasa daerah, para pemuda visioner itu memilih satu bahasa lingua franca sebagai alat komunikasi untuk menggalang perjuangan. Bahasa adalah jembatan politik.
Horizon Pembaca (Papua Selatan 2025): Bagi pemuda Papua Selatan, tantangan terbesarnya bukanlah komunikasi linguistik. Mereka fasih berbahasa Indonesia. Tantangan mereka adalah “bahasa” lain: “bahasa” modernitas. Yaitu, bahasa birokrasi yang rigid, bahasa teknologi digital, bahasa coding, bahasa manajemen proyek, bahasa keuangan, dan bahasa sains. Kesenjangan SDM (skill gap) adalah “perbedaan bahasa” yang sesungguhnya.[13]
Di saat dunia berbicara “bahasa” Industri 4.0, kesenjangan digital di Papua masih nyata. Akses internet yang terbatas di wilayah pedalaman Mappi atau Asmat menciptakan “perbedaan bahasa” baru yang menghambat partisipasi.[14] Mentalitas yang masih “PNS-sentris” juga menjadi problem, seolah “bahasa” kewirausahaan atau skill vokasi teknis bukanlah bahasa yang prestisius untuk dipelajari.[15]
Fusi Horizon (Makna Baru): Inilah fusi horizon yang paling transformatif dan mendesak. Ikrar “Satu Bahasa” harus dibaca ulang sebagai sumpah untuk menguasai “bahasa” kompetensi. “Menjunjung bahasa persatuan” hari ini berarti sebuah ikrar kolektif dan individual dari setiap pemuda Papua Selatan untuk berperang habis-habisan melawan ketidaktahuan, keterbatasan keterampilan, dan kesenjangan digital.
Ini adalah sebuah manifesto pendidikan. Sumpah ini menjadi api yang membakar semangat untuk belajar, berlatih, dan meng-upgrade diri tanpa henti. Jika para pemuda 1928 berani menyingkirkan ego kedaerahan demi bahasa persatuan, pemuda Papua Selatan hari ini harus berani menyingkirkan rasa minder, kemalasan, dan mentalitas “menunggu” demi menguasai “bahasa” baru ini. Ini bukan lagi sekadar janji, ini adalah strategi bertahan hidup dan strategi kemenangan. Menguasai “bahasa” kompetensi adalah satu-satunya cara untuk merebut kembali “tanah air” (Fusi I) dan mewujudkan “keadilan” dalam “satu bangsa” (Fusi II).
Sumpah yang Hidup
Membaca Sumpah Pemuda dengan kacamata Gadamarian menunjukkan bahwa teks itu tidak mati. Ia hidup, bernapas, dan relevan, jika kita berani berdialog dengannya. Bagi para pemuda Papua Selatan, Sumpah Pemuda 1928 bukanlah sekadar cerita sejarah tentang para Jong di Batavia.
Sumpah Pemuda adalah cermin. Sumpah Pemuda adalah proyeksi perjuangan.
Satu Tanah Air adalah sumpahmu untuk menjadi Tuan di negerimu sendiri, menjadi subjek pembangunan, bukan objek yang terpinggirkan. Satu Bangsa adalah sumpahmu untuk menuntut keadilan, menagih solidaritas, dan memastikan pembangunan ini adalah tentang martabatmu, bukan sekadar infrastruktur. Satu Bahasa adalah sumpahmu yang paling personal: sumpah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai senjatamu untuk memenangkan masa depan.
Sumpah Pemuda bukan naskah tua. Di tanah Papua Selatan, ia adalah Manifesto Revolusi Sumber Daya Manusia. Kobarkan apinya.
Daftar Pustaka
Abdullah, Taufik, ed. Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012.
Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. Jakarta: BPS, 2024.
Cahya, A. D., dan S. Wibowo. “Dampak Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan terhadap Kesiapan Sumber Daya Manusia Lokal.” Jurnal Studi Pembangunan Papua 4, no. 1 (2024): 45-62.
Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Diterjemahkan oleh Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall. Edisi ke-2 rev. New York: Continuum, 2004.
Hardiman, F. Budi. Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Gadamer. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
Hobsbawm, Eric, dan Terence Ranger, ed. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Kusumah, D., R. Sihotang, dan A. Wijaya. “Pola Pembangunan Top-Down dan Resistensi Masyarakat Adat terhadap Proyek Infrastruktur di Papua.” Jurnal Sosiologi Pedesaan 11, no. 1 (2023): 33-47.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). “Tantangan Generasi Muda Papua di Era Otonomi Khusus: Pendidikan, Keterampilan, dan Pasar Kerja.” Jakarta: LIPI Press, 2021.
Mote, S., B. K. Watory, dan L. F. Anggraini. “Tantangan Implementasi DOB di Papua: Kajian Kesiapan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan.” Jurnal Kebijakan Publik Indonesia 9, no. 2 (2023): 112-125.
Prasetijo, Adi. “Orang Asli Papua (OAP) di Persimpangan Modernisasi: Antara Afirmasi dan Marginalisasi.” Jurnal Antropologi Indonesia 38, no. 2 (2017): 145-160.
Suryawan, I Ngurah. Api di Tanah Papua: Relasi Kuasa, Etnisitas dan Perlawanan. Yogyakarta: Gading Publishing, 2019.
Widjojo, Muridan S. Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future. Jakarta: LIPI Press & Yayasan Obor Indonesia, 2009.
[1] Eric Hobsbawm dan Terence Ranger, ed., The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). Konsep ini menjelaskan bagaimana banyak “tradisi” yang terasa kuno sebenarnya diciptakan secara sadar untuk tujuan kohesi nasional.
[2] A. D. Cahya dan S. Wibowo, “Dampak Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan terhadap Kesiapan Sumber Daya Manusia Lokal,” Jurnal Studi Pembangunan Papua 4, no. 1 (2024): hlm. 46-50.
[3] S. Mote, B. K. Watory, dan L. F. Anggraini, “Tantangan Implementasi DOB di Papua: Kajian Kesiapan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan,” Jurnal Kebijakan Publik Indonesia 9, no. 2 (2023): hlm. 112-125.
[4] Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, terj. Joel Weinsheimer dan Donald G. Marshall, Edisi ke-2 rev. (New York: Continuum, 2004), hlm. 276-285.
[5] F. Budi Hardiman, Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Gadamer (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 145-152.
[6] Taufik Abdullah, ed., Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), 210-215.
[7] I Ngurah Suryawan, Api di Tanah Papua: Relasi Kuasa, Etnisitas dan Perlawanan (Yogyakarta: Gading Publishing, 2019), hlm. 78-85.
[8] D. Kusumah, R. Sihotang, dan A. Wijaya, “Pola Pembangunan Top-Down dan Resistensi Masyarakat Adat terhadap Proyek Infrastruktur di Papua,” Jurnal Sosiologi Pedesaan 11, no. 1 (2023): hlm. 33-47.
[9] Muridan S. Widjojo, Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future (Jakarta: LIPI Press & Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 115-120.
[10] Adi Prasetijo, “Orang Asli Papua (OAP) di Persimpangan Modernisasi: Antara Afirmasi dan Marginalisasi,” Jurnal Antropologi Indonesia 38, no. 2 (2017): hlm. 148-150.
[11] Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya Pasal-pasal yang mengatur tentang afirmasi OAP dalam pendidikan, kesehatan, dan perekrutan ASN.
[12] Prasetijo, “Orang Asli Papua,” hlm. 155.
[13] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Tantangan Generasi Muda Papua di Era Otonomi Khusus: Pendidikan, Keterampilan, dan Pasar Kerja” (Jakarta: LIPI Press, 2021), hlm. 88-95.
[14] Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023 (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 60-65. Laporan ini secara konsisten menunjukkan Provinsi Papua (termasuk Papua Selatan sebelum pemekaran data) sebagai wilayah dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses internet terendah.
[15] Mote, Watory, dan Anggraini, “Tantangan Implementasi DOB,” hlm. 119.