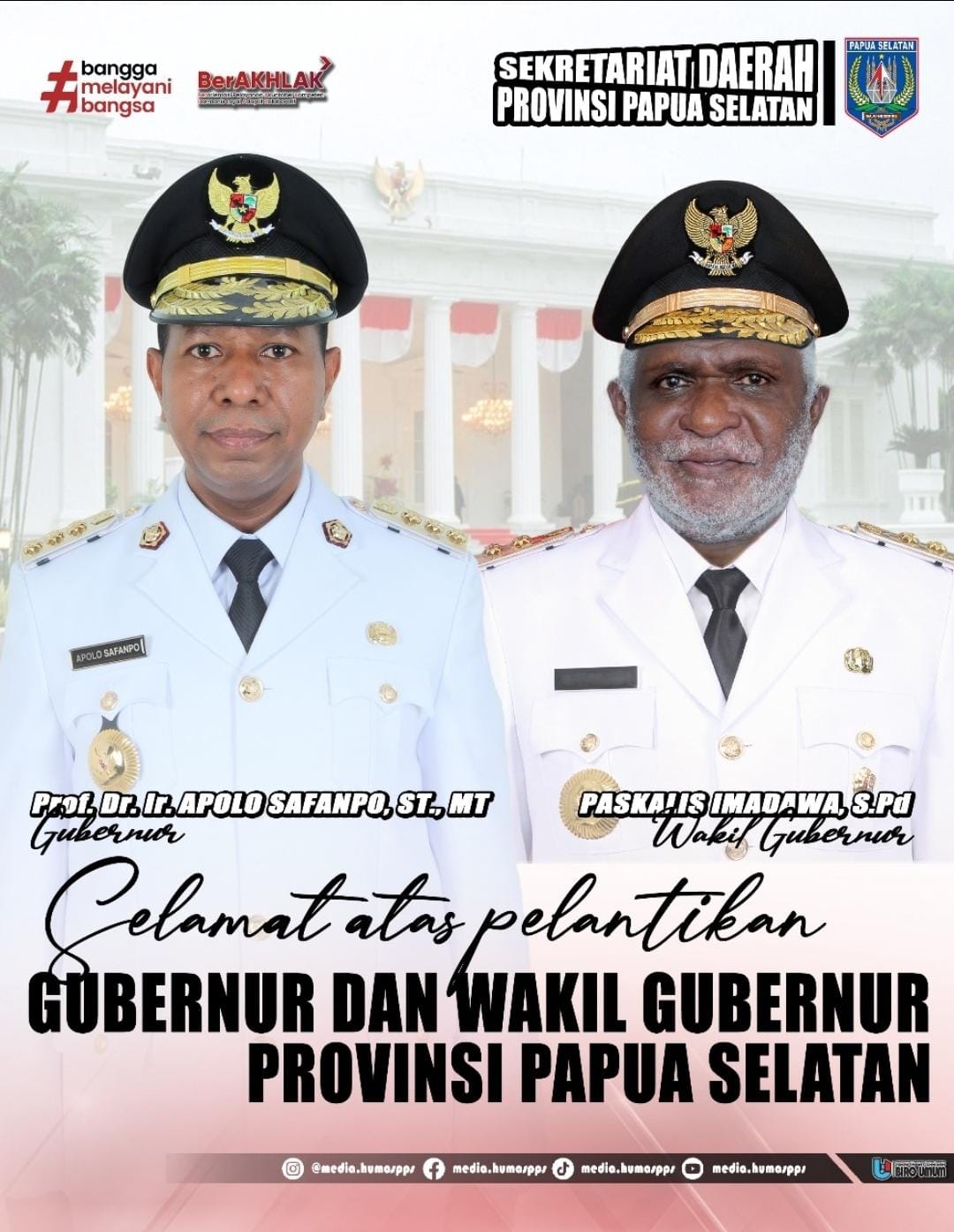Oleh : Yohanis Elia Sugianto
Sebuah rekaman video memilukan baru-baru ini beredar, mempertontonkan aparat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang membakar tumpukan mahkota adat Cenderawasih. Asap yang mengepul dari api itu bukan sekadar residu karbon dari bulu dan serat; ia adalah metafora kasat mata dari terbakarnya kepercayaan, terdesakrasinya sakralitas, dan manifestasi terbaru dari “sejarah luka” (sejarah luka) yang dialami masyarakat Papua. Api itu adalah simbol brutal dari kegagalan negara untuk melihat dengan dua mata.
Tindakan pemusnahan ini, yang diklaim sebagai bagian dari penegakan hukum konservasi, adalah sebuah tragedi profesional dan intelektual. Ia mendemonstrasikan bagaimana sebuah institusi negara dapat beroperasi dalam kebutaan budaya yang parah, menerapkan hukum positif secara kaku (rigid) tanpa sedikit pun kepekaan terhadap the living law (hukum yang hidup) di masyarakat.
Kritik utama dalam opini ini sederhana: BBKSDA telah bertindak tidak profesional bukan karena mereka menegakkan hukum konservasi, tetapi karena mereka menegakkannya dengan kacamata kuda—sebuah monokularitas yuridis yang hanya mengakui eksistensi hukum negara (hukum konvensi/positif) dan secara sadar (atau tidak sadar) mengabaikan total eksistensi hukum adat. Esai ini akan menguraikan kegagalan profesional tersebut, sebelum beralih ke proposal preventif yang berakar pada pluralisme hukum, dan diakhiri dengan langkah-langkah resolusi damai yang konstruktif untuk memulihkan luka simbolik yang telah terjadi.
Kegagalan Profesionalisme: Monokularitas Hukum Positif
Dalam optik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), apa yang mereka lakukan adalah prosedur standar operasional (SPO) yang sah. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, burung Cenderawasih adalah satwa yang dilindungi. Mahkota yang terbuat dari bulunya adalah corpus delicti, barang bukti dari sebuah pelanggaran. Dalam logika birokrasi penegakan hukum, barang bukti ilegal harus dimusnahkan agar tidak kembali masuk ke dalam sirkulasi pasar gelap.
Pendekatan ini adalah contoh sempurna dari cara pandang positivisme hukum yang murni, sebagaimana diartikulasikan oleh para pemikir seperti Hans Kelsen. Dalam paradigma ini, hukum adalah apa yang tertulis dalam undang-undang negara; ia steril dari moralitas, sosiologi, dan dalam kasus ini: antropologi. Masalahnya, Papua bukanlah ruang hampa budaya. Aparat BBKSDA tidak beroperasi di laboratorium steril, melainkan di salah satu lanskap budaya paling kompleks di planet ini.
Di sinilah letak ketidakprofesionalan itu. Profesionalisme seorang aparatur negara di wilayah yang kaya secara budaya seperti Papua tidak hanya diukur dari kemampuannya menghafal pasal-pasal dalam UU, tetapi juga dari kemampuannya membaca realitas sosial-kultural tempat ia bertugas. Kegagalan membaca realitas ini, atau yang oleh James C. Scott sebut sebagai visi negara yang “menyederhanakan” (seeing like a state), telah mengubah tindakan penegakan hukum menjadi tindakan kekerasan simbolik.
Bagi masyarakat adat Papua, mahkota Cenderawasih bukanlah “offset” atau “barang sitaan”. Ia adalah benda sakral (sacred object). Ia adalah perpanjangan identitas, simbol status kepemimpinan (ondoafi), medium spiritual, dan inti dari martabat kolektif. Dalam etnografi klasik Papua, material budaya seperti ini tidak pernah dipisahkan dari alam gaib dan tatanan sosial. Membakar mahkota tersebut di muka publik tidak ubahnya dengan membakar salib di depan gereja atau merobek Al-Quran di depan masjid. Itu adalah sebuah desecration: penodaan yang disengaja.
Tindakan memilih “api” sebagai metode pemusnahan memperburuk cedera ini. Dalam banyak kosmologi, api adalah elemen pemurni untuk melenyapkan sesuatu yang “kotor” atau “jahat”. Dengan membakar mahkota Cenderawasih, negara melalui tangan BBKSDA, secara simbolik mengomunikasikan bahwa simbol keluhuran tertinggi Orang Asli Papua (OAP) adalah sesuatu yang “kotor” dan “ilegal” yang harus dimurnikan oleh api birokrasi.
Ini adalah kegagalan institusional yang berakar pada pengabaian pluralisme hukum. Teori hukum telah lama bergerak melampaui positivisme kaku. Pemikir seperti Eugen Ehrlich mengingatkan kita akan “hukum yang hidup” (living law), yang eksis berdampingan dan seringkali lebih kuat daripada hukum negara. Di Indonesia, realitas ini diakui secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
BBKSDA, sebagai perpanjangan tangan negara, telah gagal total dalam menjalankan amanat konstitusional ini. Mereka bertindak seolah-olah hukum adat Papua tidak ada, atau setidaknya, tidak relevan jika dibandingkan dengan supremasi UU Konservasi. Inilah puncak dari arogansi birokratik: menganggap hukum adat sebagai “folklor” belaka, bukan sebagai sistem normatif yang setara dan sah yang mengatur kehidupan jutaan manusia.
Tindakan Preventif: Mengoperasionalkan Pluralisme Hukum
Polemik ini adalah alarm kebakaran. Jika tidak ada perubahan fundamental dalam cara negara berinteraksi dengan adat, insiden serupa akan terus terulang. Permintaan maaf tidak cukup; yang dibutuhkan adalah reformasi prosedural yang mengakar. Tiga langkah preventif fundamental harus segera dirumuskan:
- Pertama, formalitas konsultasi melalui Standard Operating Procedure (SOP) berbasis Adat. Harus ada Nota Kesepahaman (MoU) yang mengikat antara Kementerian LHK/BBKSDA dengan lembaga representasi kultural Papua, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat di setiap wilayah. MoU ini harus melahirkan SOP baru: “Prosedur Penanganan Barang Sitaan Konservasi Bernilai Sakral Adat.” SOP ini harus menyatakan bahwa setiap barang sitaan yang memiliki status-ganda (ilegal secara hukum negara, sakral secara hukum adat) dilarang dimusnahkan. Prosedur ini harus mewajibkan BBKSDA untuk segera menghubungi MRP atau Dewan Adat terkait untuk menentukan disposisi (penanganan akhir) barang tersebut. Ini adalah praktik standar dalam yurisdiksi yang menghargai pluralisme hukum, di mana sistem hukum negara dan sistem hukum adat berinteraksi melalui “persimpangan” yang terlembaga (legal interfacing).
- Kedua, mengubah paradigma dari pemusnahan menjadi alih-fungsi (Repurposing). Solusi yang disuarakan oleh banyak tokoh Papua adalah yang paling logis: mahkota sitaan itu seharusnya diserahkan ke museum (seperti Museum Negeri Papua) atau disimpan di Rumah Adat (Rumah Kultural) yang ditunjuk. Langkah ini mencapai dua tujuan sekaligus secara elegan. Dari sisi konservasi, barang tersebut telah “dinetralkan”, ia ditarik dari pasar gelap dan tidak dapat diperjualbelikan. Dari sisi adat, bend, tersebut dihormati. Ia dialihkan dari “barang bukti kejahatan” menjadi “Benda Cagar Budaya” (cultural heritage). Ia dapat menjadi materi edukasi yang kuat bagi generasi muda Papua tentang pentingnya konservasi sekaligus keluhuran adat mereka. Dengan demikian, UU Konservasi dan Hukum Adat tidak saling menegasi, melainkan saling menguatkan.
- Ketiga, pembinaan kompetensi kultural bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak dapat diterima jika ASN yang ditugaskan di Papua (baik OAP maupun non-OAP) tidak memiliki pemahaman dasar mengenai antropologi dan hukum adat setempat. Pelatihan “Kompetensi Kultural Lintas-Budaya” harus menjadi syarat wajib bagi setiap aparat yang bertugas di wilayah adat yang sensitif. Mereka harus dilatih untuk melihat dengan “visi binokular”, satu mata pada hukum positif, satu mata lagi pada hukum adat. Tanpa kompetensi ini, mereka akan selamanya menjadi agen negara yang “asing” (alien) di tanah tempat mereka bekerja.
Langkah Konstruktif: Menyembuhkan Luka Simbolik
- Untuk polemik yang sudah terjadi, tindakan preventif saja tidak cukup. Ada luka simbolik yang nyata dan harus segera ditangani secara damai dan konstruktif. Permintaan maaf dari Kepala BBKSDA adalah langkah awal yang baik, namun dalam konteks Papua, itu belum memadai. Karenyanya perlulah untuk diusahakan:
- Rekonsiliasi formal yang melampaui siaran pers. Pimpinan BBKSDA dan perwakilan aparat yang terlibat harus secara proaktif meminta waktu untuk “duduk bicara” (duduk adat) dengan para pimpinan MRP (khususnya Papua Selatan) dan Dewan Adat Saireri. Ini bukan forum untuk membela diri atau berdebat yuridis. Ini adalah forum untuk mendengar (listening forum). Tujuannya adalah membangun kembali relasi yang rusak, sebuah fondasi penting dalam resolusi konflik model restorative justice (keadilan restoratif) yang sangat relevan dengan budaya pasifik.
- Penyelesaian melalui mekanisme adat. Karena pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap sakralitas adat, maka pemulihannya harus melalui hukum adat. Negara, melalui BBKSDA, harus bersedia “tunduk” secara simbolik pada mekanisme adat untuk memulihkan ketidakseimbangan kosmik yang telah mereka ciptakan.
Apakah ini berarti pembayaran denda adat (customary fine), pelaksanaan upacara bakar batu sebagai simbol perdamaian, atau ritual pembersihan lainnya, harus diserahkan sepenuhnya kepada para tetua adat untuk menentukannya. Bagi negara, tindakan tunduk pada prosesi adat ini bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kemenangan besar. Ini adalah cara paling ampuh untuk secara publik mengakui eksistensi dan validitas hukum adat Papua, sesuai amanat Pasal 18B UUD 1945. Ini akan menjadi preseden kuat bahwa di Indonesia, hukum adat dan hukum negara dapat berjalan beriringan.
Penutup
Api yang membakar mahkota Cenderawasih di Papua adalah api peringatan. Ia menunjukkan bahaya laten dari arogansi birokrasi yang memandang hukum secara monokular. Insiden ini membuktikan bahwa penegakan hukum konservasi yang mengabaikan hak-hak dan kearifan masyarakat adat (indigenous rights) adalah sebuah bentuk baru “kolonialisme hijau” (green colonialism) yang pasti akan gagal.
Konservasi di Tanah Papua tidak akan pernah berhasil jika dilakukan melawan masyarakat adat. Konservasi hanya akan berhasil jika dilakukan bersama masyarakat adat, sebagai mitra yang setara. Langkah pertama untuk mencapai kemitraan itu adalah memadamkan api arogansi dan mulai belajar melihat dengan dua mata: mata hukum negara, dan mata kearifan adat.
Daftar Pustaka
Benda-Beckmann, Franz von, dan Keebet von Benda-Beckmann. “Social Security and Legal Pluralism.” Dalam Social Security in Developing Countries. London: Routledge, 1994.
Chauvel, Richard. Constructing Papua: From Special Autonomy to Declaration of Independence. Washington, DC: East-West Center, 2020.
Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.
Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, 1963.
Griffiths, John. “What is Legal Pluralism?” Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 24, no. 1 (1986): 1-55.
Haar, B. Ter. Adat Law in Indonesia. New York: Institute of Pacific Relations, 1948.
Hall, Edward T. Beyond Culture. New York: Anchor Books, 1976.
Holleman, J. F., ed. Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
Knauft, Bruce M. South Coast New Guinea Cultures: History, Comparison, Dialectic. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Koentjaraningrat. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1971.
Lederach, John Paul. The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Sekretariat Negara, 1990.
Scott, James C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998.
Sillitoe, Paul. Made in Niugini: Technology in the Highlands of Papua New Guinea. London: British Museum Press, 1988.
Smith, Laurajane. Uses of Heritage. London: Routledge, 2006.
Tsing, Anna L. Friction: An Ethnography of Global Connection. Princeton: Princeton University Press, 2005.